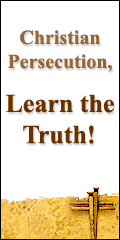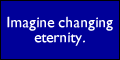|
In Memoriam Paus Yohanes Paulus II, Ujung Mortalitas
Oleh: B. Herry-Priyono
Saturday, Apr. 9, 2005 Posted: 12:23:30PM PST

Gerbang mortalitas di Basilika Santo Petrus menganga. Ke dalamnya jenazah Paus Johanes Paulus II akan meletak. Tirai suatu era telah turun, dan jeda sejarah beberapa hari mendatang akan berisi kenangan tentang suatu kurun. Di luar Basilika, para peziarah nampak seperti yatim piatu yang tertawan rasa kehilangan. Mortalitas adalah ciri hidup yang bisa mati. Sebuah sosok telah tiba di ujung mortalitas, untuk kemudian tenggelam ke masa silam. Dayanya untuk kehidupan tidak lagi tertangkap melalui mata, melainkan lewat sungai rasa.
Siapakah orang ini, sehingga kepergiannya telah membuat para peziarah tampak seperti piatu? Simulacra media telah menampilkan kisahnya dengan ketelitian membelah sehelai rambut menjadi tujuh. Ia seorang yang lahir di Polandia, mencecap penderitaan di bawah rezim Nazi dan Tirai Besi, ia dramawan dan olahragawan, seorang imam dan uskup yang entah suka atau terpaksa menjadi Paus, pemimpin Gereja Katolik. Ia datangi begitu banyak kota dan negara pada bola dunia, ia masuk mesjid, sinagoga, dan kuil untuk memperbaiki hubungan yang hancur oleh perbedaan agama, ideologi, ekonomi, maupun adat. Ia memegang tradisionalisme moral yang mirip ajaran Abad Petengahan: tentang kontrasepsi, aborsi, keluarga dan sebagainya. Seperti setiap manusia, ia berisi ambivalensi.
Lalu, dalam beberapa bulan terakhir ini, tatkala panah mortalitas mencegatnya, ia masih menyulut kontroversi. Untuk kinerja kepemimpinan modern, ketetapannya untuk tidak mengundurkan diri meskipun sudah renta menjadi keganjilan. Lalu orang bertanya, apakah ia haus kekuasaan? Apakah ia tidak tahu manajemen? Apakah ia hantu masa lalu? Kemudian, ia membiarkan tubuhnya yang sakit dan renta menjadi pemandangan mata seluruh dunia. Pada akhirnya, hari-hari dan jam-jam terakhir hidupnya menjadi kisah paling global tentang kematian seorang manusia. Kepemimpinan adalah jalan kesunyian. Tetapi memimpin dunia tentang cara memeluk puncak mortalitas adalah kelangkaan.
Mungkin di situlah terletak pesan paling mendalam dari manusia yang kini terbaring di bawah kubah Basilika itu. Dan pesan itu hanya terdengar nyaring apabila dihadapkan dengan pandangan tentang ‘penderitaan’ (suffering) dalam cuaca kultural dewasa ini. Genius teknologi telah mengangkat anak-anak modernitas dan pasca-modernitas menjadi generasi yang makin lentur mengelak dari apa saja yang terasa menyiksa. Aneka genius teknologi, dari teknologi rumah tahan gempa sampai teknologi komunikasi, yang telah meringankan ratusan ribu korban tsunami adalah bukti. Tetapi sesudah semua itu, penderitaan ternyata senantiasa mengalami metamorfosa ke dalam bentuk-bentuknya yang baru.
Dalam pertempuran antara pengelakan dari penderitaan dan permanensi penderitaan itulah cuaca kultural dewasa ini tegak berdiri. Dibantu ajaran-ajaran psikologi populer dan konsumerisme, berkembang semacam cuaca kultural yang menganggap penderitaan sebagai tabu. Mungkin justru karena dilihat tabu, penderitaan menjelma menjadi daya ajaib yang dijauhi sekaligus dicari.
Lewat teknologi simulacra di media, ia hadir agar menggerakkan simpati, namun penderitaan lebih sering berakhir menjadi objek kanibalisasi. Maka penderitaan tampil dengan wajah yang makin seram, seperti sosok abadi laknat dan kejahatan. Semakin ia tidak diakui sebagai bagian kondisi kehidupan, semakin ia menampilkan diri sebagai kutuk yang menakutkan.
Spiral pertarungan berikutnya berlangsung di depan mata. Semakin kita menemukan cara-cara baru mengelakkan penderitaan, semakin penderitaan tampil dengan wajah baru, dan fakta mortalitas semakin tampil mengancam bagai kutuk kehidupan yang tabu.
Next Page: 1 | 2 | 3 |
|