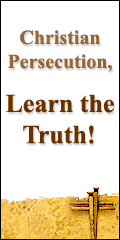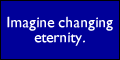|
Membebaskan PGI dari "Kecanduan" pada Penguasa
Saturday, Dec. 11, 2004 Posted: 5:09:56PM PST

Kita patut bersyukur, karena Sidang Raya XIV Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (SR XIV PGI) sudah berakhir dengan baik, Minggu (5/12/2004). Pada hari itu juga sudah ditetapkan Andreas A Yewangoe sebagai ketua umum berikut "kabinet"-nya.
Yewangoe bukanlah sosok asing. Ia sudah dikenal sangat aktif dalam mengemban misi dialog antarumat beragama dalam bingkai kemajemukan agama dan budaya. Tidak hanya itu, Yewangoe juga dikenal sebagai penulis produktif.
"Kabinet" Yewangoe terlihat padat dan kuat. Saya sebut salah satunya, Jan Sihar Aritonang, yang duduk sebagai salah satu Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI. Sama seperti Yewangoe, Aritonang juga aktif berkampanye pentingnya penegakan kerja sama antarumat beragama. Ia juga seorang penulis terandalkan.
Kedua tokoh itu, selain berprofesi sebagai pendeta dan teolog, adalah dosen teologi dengan aras kejernihan objektivitas yang tinggi. Mereka menyukai mahasiswa yang kritis terhadap kemapanan gereja dan pemerintah. Pertanyaannya, mampukah mantan dosen saya itu mempertahankan citra kritis dan objektif setelah duduk di kursi kepemimpinan PGI? Sudah barang tentu pertanyaan saya itu juga berlaku bagi para anggota "kabinet" lainnya.
Banyak orang sependapat bahwa gereja di Indonesia berada pada masa keemasannya, ketika berada di bawah rezim Orba. Suasana itu sedikit-banyak mirip dengan gereja di masa awalnya dikenal sebagai paguyuban Kristen telah menjadi lembaga agama dan menjadi anak emas ketika Kristen dijadikan agama negara pada abad IV.
Gereja menjadi kuat, apabila ada "putra gereja" yang duduk menjadi pejabat, baik di kalangan sipil maupun militer. Tidaklah penting apakah mereka itu sudah menjalankan tugas dengan baik dan benar atau tidak. Yang penting adalah "putra gereja" dan memberikan rasa aman pada gereja. Aman di sini mencakup dua hal: aman beribadah dan aman pendanaan.
Rasa aman ini makin ternyatakan lewat bagaimana pejabat negara ini masuk dalam struktur PGI. Sudah menjadi kebiasaan buruk (bad habit), apabila ada suatu acara atau rapat gerejawi, "putra gereja" ini diberi kehormatan memberikan pidato pengarahan, yang bukan sekadar kata-kata sambutan.
Aneh, PGI yang mestinya membawa jeritan suara jemaat disulih dengan arogansi penguasa. Sejumlah teolog kritis yang menjadi langganan duduk di kepengurusan PGI hanya bisa manggut-manggut. Konyolnya lagi ada seorang teolog senior yang sangat berpengaruh justru menyalahkan gereja yang tidak mau memanfaatkan talenta dan profesionalitas "sang putra gereja".
Bahkan ia memuja-muji "sang putra gereja" itu sebagai pejabat yang berhati pendeta (lihat Gereja dan Kontekstualisasi, Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm. 125-146). Mestinya teolog itu mempertanyakan kepada "sang putra gereja" apakah ia "menggarami" atau justru "digarami" dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan? Setidaknya ditanyakan dari manakah asalnya sejumlah besar uang yang dihibahkan kepada gereja? Jangan-jangan gereja sudah menjadi tempat money laundering paling aman di dunia?
Saya sendiri tidak dapat memberikan jawaban apakah di era Orba gereja sengaja mengambil sikap dan posisi sebagai anak manis ataukah gereja memang tidak berdaya untuk dijadikan anak manis oleh penguasa dari kalangan "putra gereja". Berpindahnya gereja dari era Orba ke era Reformasi sebenarnya mirip lepasnya kekuasaan Jepang atas Indonesia akibat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Sekutu.
Next Page: 1 | 2 |
Eva N.
|